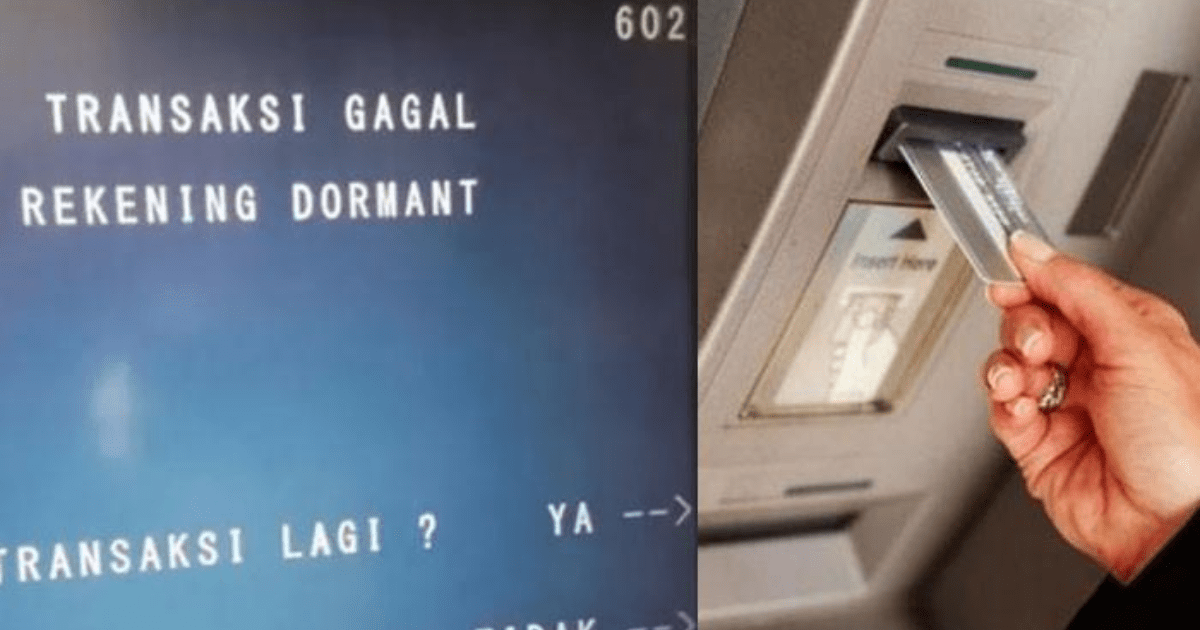Retconomynow.com – 28 Oktober 2025 – Sebuah pernyataan kontroversial datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengklaim, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menahan laju ekonomi 5 persen di Indonesia. Menurutnya, setiap kali pertumbuhan mendekati 6 persen, ada yang sengaja “menginjak rem” dengan alasan ekonomi kepanasan (overheating). Pernyataan ini sontak memicu perdebatan sengit. Faktanya, para ekonom justru melihat masalah yang lebih fundamental. Bukan konspirasi, melainkan problem struktural yang telah lama membelenggu perekonomian nasional.
Tesis Menkeu Purbaya: “Penghambat” Pertumbuhan dan Janji Pembasmian
Dalam sebuah dialog ekonomi, Menkeu Purbaya melontarkan sebuah tesis yang sangat berani. Ia melihat stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen selama bertahun-tahun bukanlah sebuah fenomena alami. Justru, ia meyakini ada sebuah intervensi yang disengaja.
“Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita nggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini,” ujar Purbaya. “Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak,” sambungnya.
Bagi Purbaya, argumen “ekonomi kepanasan” tidak relevan selama angka pengangguran masih tinggi. Oleh karena itu, ia berjanji akan “membasmi” penghalang tersebut. Caranya adalah dengan meluncurkan program-program yang dampaknya langsung terasa oleh rakyat. Ia optimistis, dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Bahkan, ia menargetkan di tahun kelima pemerintahan Presiden Prabowo, bayangan pertumbuhan 8 persen sudah mulai terlihat.
Bantahan Pakar: Bukan Konspirasi, tapi “Keseimbangan Politik-Ekonomi”
Namun, para ekonom melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengaku tidak melihat adanya pihak yang secara sengaja mengatur laju ekonomi 5 persen. Sebaliknya, ia sepakat bahwa ada sebuah “keseimbangan politik-ekonomi” yang secara struktural membuat pertumbuhan sulit menembus batas tersebut.
Menurut Ronny, ada beberapa faktor struktural utama:
- Ketergantungan pada Konsumsi: Struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Porsinya mencapai 54-55 persen dari PDB. Sementara itu, kontribusi dari sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur bernilai tambah tinggi dan ekspor masih sangat terbatas.
- Trade-off Stabilitas vs. Pertumbuhan: Inilah yang mungkin Purbaya maksud dengan “kepanasan”. Jika pemerintah memacu pertumbuhan terlalu cepat (misalnya, melalui stimulus fiskal besar-besaran), hal itu akan menimbulkan tekanan makroekonomi. Inflasi bisa melonjak, defisit transaksi berjalan melebar, dan nilai tukar rupiah bisa terguncang. “Bank sentral dan otoritas fiskal tentu akan lebih memilih pertumbuhan yang stabil dan terkendali, daripada lonjakan cepat tapi rapuh,” imbuh Ronny.
- Resistensi terhadap Reformasi: Di sisi lain, Ronny mengakui adanya dimensi politik. Pertumbuhan tinggi menuntut adanya reformasi struktural besar, seperti efisiensi birokrasi dan perbaikan iklim investasi. Akan tetapi, reformasi seperti ini seringkali mengganggu kenyamanan kelompok kepentingan (vested interests) yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang ada. Dengan demikian, ini bukan soal ada yang sengaja menginjak rem, melainkan sistem yang cenderung mempertahankan status quo.
Akar Masalah Sesungguhnya: Kinerja Sektor Manufaktur yang Lesu
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menawarkan perspektif lain yang lebih konkret. Menurutnya, alih-alih mencari “kambing hitam”, pemerintah seharusnya fokus pada akar masalah sesungguhnya: kinerja sektor industri manufaktur yang belum optimal.
“Ketika industri manufaktur melambat, dampaknya langsung terlihat pada perlambatan ekonomi nasional. Tren sepuluh tahun terakhir menunjukkan hal ini sangat jelas,” katanya. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, kesehatan industri manufaktur adalah cerminan dari kesehatan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Rendy menyarankan agar Kementerian Keuangan, sebagai pemegang otoritas fiskal, mengambil peran strategis. Mereka bisa mendorong sektor ini melalui kebijakan insentif yang terarah. Contohnya, memberikan subsidi atau stimulus khusus bagi subsektor manufaktur yang padat karya dan berorientasi ekspor. Ia juga mengkritik fokus investasi yang selama ini masih terpusat pada hilirisasi tambang. “Investasi memang kunci untuk membawa laju ekonomi 5 persen ke atas, tapi jangan hanya di hilirisasi tambang. Perlu dorongan merata ke berbagai subsektor manufaktur lain,” terangnya.
“Quick Wins” yang Bisa Dilakukan: Deregulasi dan Pemberantasan Rente
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menambahkan beberapa langkah praktis yang bisa menjadi “kemenangan cepat” (quick wins) bagi pemerintah. Daripada menyalahkan pihak yang tidak jelas, Riefky menyarankan pemerintah untuk fokus pada reformasi internal.
Salah satunya adalah deregulasi besar-besaran. “Salah satu program yang menurut saya quick wins adalah deregulasi untuk mengurangi kompleksitas perizinan sehingga memicu naiknya investasi,” katanya. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas praktik perburuan rente (rent-seeking) yang masih marak dalam proses bisnis di dalam negeri. Kepastian hukum juga harus ditegakkan untuk memberikan efek jera. Pada akhirnya, Riefky juga mengkritik dominasi negara dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, hal ini justru bisa menimbulkan efek crowd-out, di mana peran swasta menjadi terpinggirkan dan investasi swasta menurun.
Kesimpulan: Jalan Menuju Pertumbuhan Tinggi Membutuhkan Reformasi Fundamental
Pada akhirnya, pernyataan Menkeu Purbaya telah berhasil memantik sebuah diskusi penting tentang arah perekonomian Indonesia. Namun, analisis para pakar menunjukkan bahwa masalah stagnasi laju ekonomi 5 persen jauh lebih kompleks daripada sekadar adanya “penghambat”. Ini adalah masalah struktural yang telah mengakar. Mulai dari ketergantungan pada konsumsi, lemahnya industri manufaktur, hingga sistem politik-ekonomi yang cenderung menghindari risiko. Dengan demikian, jalan untuk menembus pertumbuhan 6 persen atau lebih tidak bisa ditempuh hanya dengan program populis. Justru, jalan itu menuntut adanya reformasi fundamental yang berani, konsisten, dan seringkali tidak populer.